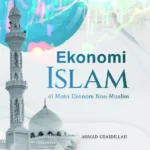Oleh: Sauqi Futaqi*
Musim Ibadah haji selalu menjadi fenomena religius yang banyak mengundang perhatian. Ada yang melihat fenomena ini sebagai bentuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Ada yang menilai fenomena ini sebagai peningakatan kualitas beragama seseorang dengan menggenapi rukun Islam yang kelima. Namun, sebaliknya, ada yang menyoroti fenomena ini justru sebagai ajang untuk menaikkan image positif dan status sosial di masyarakat dengan predikat sebutan haji yang menyertai namanya. Bahkan, lebih ekstrimnya, tidak sedikit menuding fenomena ini sebagai ajang bisnis bagi pejabat penyelenggara dan pembersihan citra negatif bagi jama’ahnya.
Meskipun sekian penilaian dan sorotan tersebut tidak selalu tepat dan akurat, namun setidaknya hal itu bisa dipandang sebagai kritik dan saran bagi peribadatan haji selama ini, sekaligus juga menjadi refleksi lebih jauh atas pertanyaan yang mengendap di kepala publik, yakni kenapa peningkatan jumlah jama’ah haji tidak selalu berbanding lurus dengan komitmen moral, tingah laku, dan sikap para jama’ah. Bahkan, bisa dihitung jari berapa jumlah pejabat yang belum naik haji, tapi kenapa korupsi dan penyalahgunaan jabatan masih banyak dijumpai. Atau mungkin berapa jumlah orang kaya muslim yang sudah berhaji, tapi masih suka menyepelekan, menghina dan menindas orang miskin.
Padahal, dalam sejarah Nusantara, fenomena haji tidak sesederhana yang kita lihat sekarang ini. Orang-orang dulu yang hendak beribadah haji selalu merasa dibebani tugas dan tanggung jawab untuk menata masyarakat. Karenanya, tidak sedikit jama’ah meluangkan waktu sambil belajar agama di sana agar sepulang dari haji dapat menjadi teladan dan mengajarkan agama kepada masyarakat. Lebih hebatnya lagi, meski kebijakan kolonial tidak menguntungkan bagi para jama’ah, mereka tetap berusaha menjalankan pesan moral agamanya sebagai orang yang sudah berhaji. Meskipun konteks sekarang tidak perlu lagi belajar disana dan tidak harus berhadapan langsung dengan kebijakan kolonial yang meresahkan, namun spirit dan pengabdiannya perlu menjadi refleksi bersama.
Masa Kolonial
Pada masa Kolonial, keseriusan para jama’ah haji ternyata melahirkan sikap anti kesewenang-wenangan. Sikap ini lama kelamaan tercium oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Bagi pejabat kolonial, haji dianggap sebagai sarana dimana spirit pemberontakan menjadi sumber imaginasi keagamaan para haji dari Nusantara. Oleh karenanya, mereka dianggap cukup berbahaya bagi misi kolonial untuk merampas hak pribumi.
Gerakan pemberontakan seperti Gerakan Padri di Sumatera Barat (1807-1832), Perang Jawa 1825-1830), pemberontakan Banten tahun 1888, Perang Aceh (1873-sekitar 1910), dan lainnya, kebanyakan dimotori dan dipimpin oleh tokoh-tokoh jama’ah haji. Dalam pemberontakan Banten, Kartodirdjo (1966:149) menilai bahwa pemberontakan mereka sejalan dengan komitmen mereka dalam upaya pembaruan orientasi syari’at demi “ penguatan sendi moral dan keagamaan masyarakat Muslim, perbaikan tingkah laku, dan usaha untuk kembali kepada cita-cita Islam dalam bentuknya yang asli”. Melihat tindakan kolonial yang mencoba mengikis rasa keadilan, para jama’ah haji berusaha menyadarkan masyarakat tentang arti keadilan dan hak asasi manusia, sehingga lahir lah perlawanan yang cukup massif demi merebut kemerdekaan.
Gerakan anti kolonial yang dimotori oleh para jama’ah haji tersebut tak urung mendapat respon cukup serius dari Pemerintah Kolonial. Para peneliti Belanda dikerahkan untuk mengkaji secara khusus aktivitas mereka, baik ketika berada di Makkah maupun sepulang dari haji, untuk memberikan pemahaman yang baik, terutama gerakan yang dicurigai membahayakan kepentingan kolonial. Akibatnya, kebijakan yang semula membatasi aktivitas Haji, diganti dengan perlakuan yang lebih halus, seperti pengangkatan status sosial mereka dan diakomodir sebagai pejabat tertentu dalam pemerintahan Kolonial. Strategi ini dilakukan untuk mencegah agar gerakan anti-kolonial tidak berjalan secara massif.
Baca Juga: Nyawa Lebih Suci dari Ka’bah
Melawan Watak Kolonial
Pada era post-kolonial seperti saat ini, tentu saja konteksnya berbeda dan barangkali perlakuan kolonial mengalami transformasi diri. Namun, pada prinsipnya watak kolonial bisa jadi masih merambah pada struktur kesadaran masyarakat post-kolonial. Seseorang bisa jadi lebih kejam dari perlakuan kolonial pada masa silam. Kita bisa lihat saat ini masih banyak orang yang suka menindas saudaranya sendiri sebagai satu bangsa (korupsi, diskriminasi, eksploitasi, dll).
Pada hakikatnya, watak kolonial merupakan sikap, prilaku, dan tindakan yang ingin menguasai dan bahkan merampas kenyamanan dan kesejahteraan orang lain. Dalam konteks saat ini, orang berhaji semestinya mampu menerjemahkan gerakan anti-kolonial pada masa itu ke dalam kehidupan riil di masyarakat saat ini. Artinya, orang berhaji tidak semestinya merasa gagah dengan kesalehan individualnya dan prestise atas gelar hajinya, melainkan berusaha untuk menjadi inspirasi dan teladan masyarakat untuk menghilangkan sikap, prilaku, dan tindakan yang berwatak kolonial.