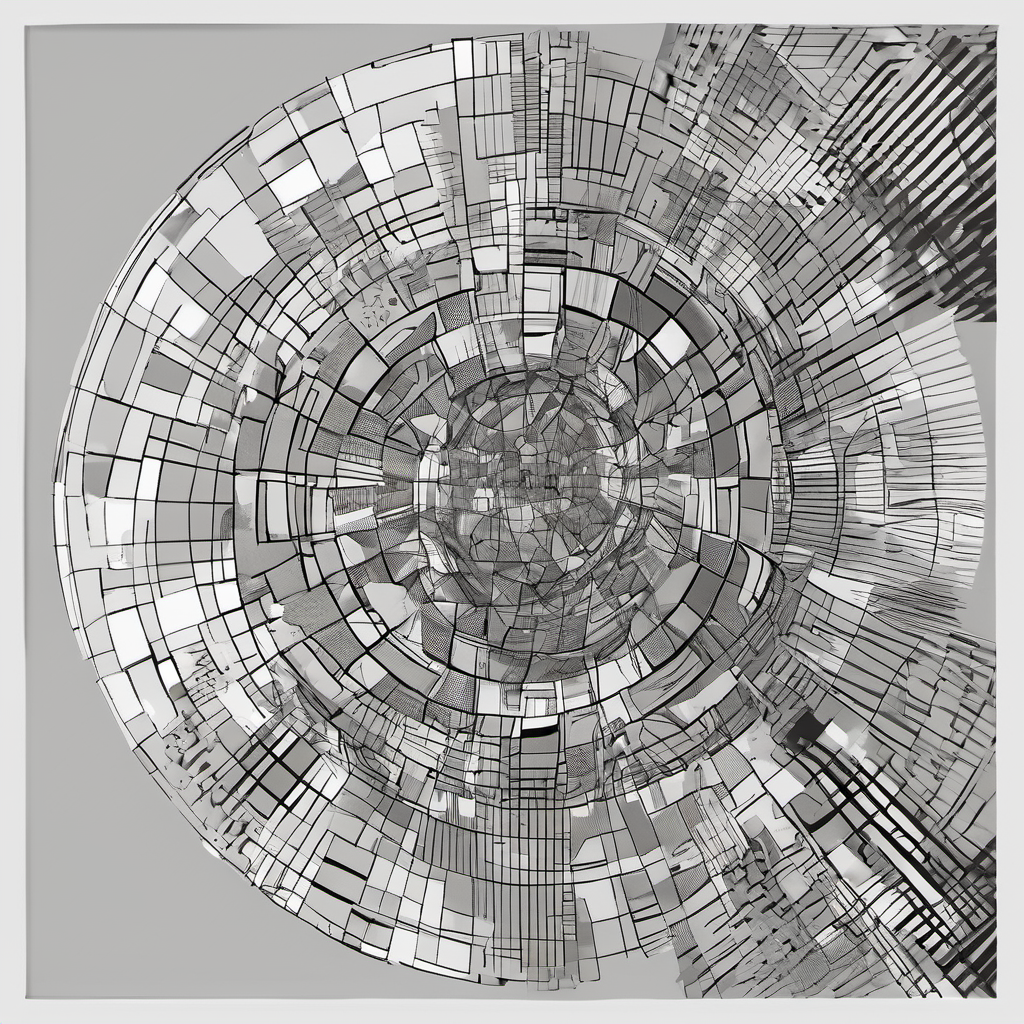Pikiran saya sebenarnya telah lama heran dengan prilaku dan gerak lembaga-lembaga pendidikan yang pernah saya temui, baik sejak di pesantren dulu maupun di tempat mengajar saya saat ini. Entah seperti ada yang kurang cocok, ngganjel di hati nurani saya. “kok sepertinya proses saya belajar tidak seperti ini ya?”, “Kok kayaknya pengetahuan yang menancap dalam di hati saya sehingga menjadi passion saya tidak melalui proses yang seperti ini ya?”.
Begitulah keheranan-keheranan yang sering saya rasakan ketika melihat atau menginjakkan kaki di sebuah lembaga pendidikan. Saya sering kepikiran apa masalahnya lembaga-lembaga pendidikan ini memang sebenarnya bukan tempat belajar?, ataukah lembaga-lembaga pendidikan ini menyalahi hakikat belajar?, ataukah standar mata pelajarannya tidak pas dengan undakan pemahaman peserta didik?, ataukah pengajarnya kurang profesional?, ataukah fasilitasnya yang belum memadahi?, atau sistem dan kurikulumnya yang tidak pas?, atau falsafah pendidikannya?, entahlah, itu masih misteri. Akan tetapi saya punya contoh kasus yang menarik yang mungkin dapat sedikit mengurai pekatnya misteri jawaban dari keheranan saya ini.
Tepatnya ketika beberapa waktu yang lalu kawan lama saya yang kini telah menjadi pengasuh sebuah pesantren di Jawatimur mengajak saya bertemu untuk bertukar pikiran mengenai program pendidikan pesantren yang ia warisi oleh Abahnya itu. Ia membawa berkas program lama untuk bahan pertimbangan. Disitulah mata saya agak terbuka sekaligus tak habis pikir, kenapa program kerja seperti mengadakan pengajian kitab kuning targetnya ditulis meningkatkan iman dan takwa santri? Bagaimana bisa diukur keberhasilannya?. Ah, ngaco semua ini. Ada lagi bidang bakat minat santri dipisahkan dari bidang pendidikan. Seolah-olah keterampilan Santri bukanlah bagian dari tugas pendidikan, sehingga ia disebut sebagai ekstra kurikuler. Sesuai pengalaman saya, dimanapun yang namanya ekstra kurikuler pastinya adalah hal sekunder, tak penting, bahkan bagi mereka yang sinis pasti akan bilang tak ada gunanya. Akhirnya pendidikan dikotakkan hanya dalam hal baca tulis. Pegiat-pegiat pendidikan seperti saya pasti kesal dan ingin merobek kertas itu dan membuangnya ke tong sampah.
Mungkin inilah masalah-masalah yang sering menjadikan saya heran dan ngganjel saat melihat lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya pesantren yang sok-sokan membawa identitas modern. Tak jelas secara filosofi, tak jelas ideologi, tak punya strategi, akhirnya minim loyalitas dan tak ada hasil. Paradigma kurikulumnya gaya positivistik Barat, tapi langkah dan perilakunya masih klemar-klemer khas Timur. Padahal sebenarnya Baratnya tak benar-benar Barat, toh rancang bangunnya tentang masalah program, tujuan dan indikator pencapaian saja tak logis. Timurnya pun tak benar-benar timur. Kalau mencaci orang lain kritisnya minta ampun, tapi pada diri sendiri suka memaklumi, dengan beranggapan semua takdir Tuhan. “Paradigmanya Barat, prilakunya Timur, Hatinya Zimbabwe”, Ucap kawan saya berseloroh.
Saya berharap kita bisa konsekuen dengan paradigma yang kita ambil. Jika kita sudah mantap memakai positivisme Barat, ya jangan ragu untuk menegur orang-orang yang ikut andil dalam mandeknya instrumen proses. Jangan lagi bawa-bawa sopan-santun ketimuran padahal dalam hati mencaci-maki. Semuanya harus profesional dan setara dalam hak dan kewajiban. Apakah ini akan berhasil dengan baik di lingkungan kita yang timur? Itu lain soal. Saya hanya mewanti-wanti, jika kita tidak konsekuen maka kita tidak akan kemana-mana. Tak pernah maju. Yang kita praktikkan bukanlah teori, tapi praktik para orang-orang terdahulu yang tidak mungkin bisa kita mintai pertanggungjawaban atas kebodohan dan kemalasan kita sendiri.
Kenapa tidak pakai pendidikan khas Timur saja?, jawabannya ya karena negara tak mau mengeluarkan ijazahnya. Sekolah ada standarnya, guru ada standarnya, gedung sekolah ada standarnya, bahkan tingkat materi pelajaran ada standarnya yang semuanya diatur oleh negara. Bayangkan saja komunitas-komunitas literasi kecil-kecil yang memiliki andil besar dalam perkembangan pemikiran dan wawasan generasi muda, yang nyatanya bisa lebih produktif daripada di sekolah, tidak pernah dipandang sebagai instrumen pendidikan nasional yang anggarannya dua puluh persen anggaran belanja negara. Entah siapa yang memulainya sehingga dunia pendidikan kita terdikotomikan dari segala aspeknya. Baik dari sisi pengajar, siswa, gedung, bahkan materi pelajarannya.
Pendidikan kita seolah kehilangan jatidiri. Padahal bapak-bapak pendidikan kita telah mempelopori pendidikan kita mulai dari aspek filosofis hingga praksis. “Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, semua waktu adalah belajar”, Kata Ki Hajar Dewantara.
Baca juga: Menggali Modal Multikultural Pesantren
Disamping itu dunia modern yang di tempat kelahirannya sudah banyak dikecam agaknya baru akan menemui puncaknya di Indonesia. Itulah salah satu kelucuan bangsa kita, gampang katutan tapi tidak up to date . Suka meniru hal baru tapi tidak sadar akan nilai apalagi dampak psikologis. Ngejar upo ninggal tumpeng. Sebab saya rasa pendidikan manusia tidak sepositivistik itu. Banyak faktor, banyak instrumen-instrumen yang hanya Tuhan yang tahu. Sudah sepantasnya manusia undur diri dari kata “mencetak”. Hanya Tuhan yang punya cetakan manusia. Masalah Free will dan determinisme saja masih menjadi perdebatan yang tak pernah usai, kok dengan congkaknya pendidikan modern memunculkan istilah “jaminan mutu”. Seolah ia yang menggoreskan tintanya di lauh mahfudz. Dari dulu falsafah hidup Jawa khususnya sangat erat dengan nilai-nilai sufistik, nilai kesabaran, kepasrahan dan kerendahan hati, sangat lekat dengan dengan istilah tirakat. Tapi entah sejak kapan dan dari mana asalnya akhir-akhir ini kita dicekoki dengan tren-tren dan jargon-jargon “kita bisa, kita mampu”, “Indonesia tangguh”, dan semacamnya. Jargon ini masuk di semua lini dan sektor-sektor lahan usaha para motivator dan trainer-trainer. Lini ekonomi dan bisnis jelas kena, lini pendidikan juga kena, “SMK BISA”, misalnya. Apalagi lini sosial percintaan, “boleh patah hati, tapi ingat kamu juga istimewa”, dan banyak lagi jargon-jargon kecongkakan dunia modern. Padahal jika kita mau jujur bullshit dengan semua kemampuan kita. Kita hanya punya andil kehendak, itupun kadang kita tak tahu darimana kehendak dan kemauan kita berasal. Sumber-sember inspirasi pemikiran datang begitu saja dari dunia antah brantah. Adapun andil secara real kita sebenarnya tak punya. Coba pikirkan, energi yang menggerakkan anggota tubuh kita saja, tak tahu dari mana. Ketika energi sudah terkuras dengan istirahat dan tidur energi kita kembali. Semua diberikan Tuhan secara Cuma-Cuma tanpa kita ikut mengaturnya. Sekali lagi kita hanya memiliki kehendak. Katanya “kita bisa!”, saya tanya kita bisa apa?. Justru kita menjadi sangat rapuh ketika menuruti jargon-jargon tersebut. Sebab sejatinya manusia tidak mengada untuk dirinya sendiri. Ia sedang berjalan menuju sesuatu yang lebih besar melebihi semesta. Ketika ambisinya berteriak-teriak, mendobrak-dobrak keseimbangan dan batasan-batasan semesta, matilah ia. Mati secar fisik maupun mental. Kehilangan harapan, kehilangan orientasi, menuju kehampaan dengan skeptisisme yang akut. Hancur lebur tak tersisa.
Tentu saya menyatakan hal ini bukan atas dasar pengetahuan tentang seluk-beluk sistem maupun psikologi pendidikan Indonesia. Justru sebaliknya, karena saya tidak tahu dan ingin mencari tahu lebih dalam. Saya tidak mau kita terjebak dalam kejumudan berfikir sehingga ikut-ikut saja dengan arus besar modernisasi tanpa terlebih dahulu menimbang dan memilah.
Dari pertemuan dengan kawan saya ini saya mendapat banyak hal, kebahagiaan, kesan, pelajaran, dan pemahaman. Saya terkesan karena mendapati orang yang dalam usia mudanya sudah mendapat beban tanggung jawab yang besar. Saya bahagia bertemu kawan lama yang sekarang telah menjadi seorang yang berpengaruh. Pelajaran bahwa hidup memang tak pernah menunggu kita siap dan mampu, kita dituntut untuk selalu berani menghadapi setiap kemungkinan. Dan tentunya pemahaman sementara dari keheranan-keheranan saya sebelumnya. Tapi saya juga mendapatkan satu hal lain yang tak pernah saya duga sebelumnya. Coba perhatikan apa yang ia ucapkan sesaat akan mengakhiri pertemuan setelah diskusi panjang lebar dan revisi program.
“Terimakasih telah menemani saya berfikir, juga atas masukan-masukannya. Mungkin sampeyan punya kebutuhan apa bilang saja, siapa tahu saya bisa bantu”. Lah, ini yang disebut simbiosis mutualisme dalam ranah jaring laba-laba sosial. Tak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan manusia lain. Disinilah titik perkongsian antara paradigma pemikiran dan uang ada. Lebih jelasnya hubungan paradigma pendidikan dengan bisnis “perketelaan” berbasis pesantren. Bagaimana bisa seperti ini?
Diakui maupun tidak dunia manusia memang serumit itu. Kadang manusianya sendiri saja tidak paham secara jelas kenapa demikian yang terjadi di hidupnya. Manusia adalah makhluk rasional, makhluk sosial, makhluk berkebutuhan, makhluk lemah, makhluk licik, makhluk berperasaan, makhluk yang suka penasaran, makhluk berpengharapan, dan lain-lain, yang semuanya terikat atas dasar kepentingan.
Secara kasar bisa dikatakan hubungan manusia hanyalah “tukar tambah kepentingan”. Tak ada yang namanya ketulusan, yang ada hanyalah hegemoni kepentingan dan kebahagiaan masing-masing individu. Saya memuji Tuhan atas semua ini. Dari individu personal menjadi jalinan rajutan benang sosial. Kita mempunyai seorang teman, ia juga mempunyai teman yang akhirnya menjadi teman saya. Hubungan ini terus menjalar hingga membentuk seperti jaring laba-laba. Kuat lemahnya jaringan ini ditentukan kuat dan lemahnya kepentingan yang mengisi hubungan tersebut. Kenapa jalinan hubungan kita dengan teman atau pasangan menemui kegagalan atau keterputusan? Jawabannya sederhana, sudah tidak ada kepentingan disana. Ah, dunia begitu aneh dan sekaligus sungguh indah. Dikatakan bahwa “kemajemukan dunia dan seisinya menunjukkan ke-Esa-an Tuhan”, saya baru paham sekarang.
Hubungan sosial semacam inilah agaknya yang mengilhami para kritikus dalam menyerang suatu gagasan pemikiran lawannya. “Penelitian anda didanai oleh pejabat A, pantas saja buah pemikiran anda penuh unsur politis dan cenderung berpihak padanya!”. Atau lebih ekstrim, “Pemikiran anda pasti dipengaruhi oleh kedekatan anda dengan si B, sehingga tak mengherankan jika ditujukan untuk memobilisasi masa agar mendukung si B dalam menggulingkan si A”. Apakah benar demikian? Mungkin ya, mungkin tidak. Artinya, kita tidak bisa mengklaim secara sepihak tentang orisinalitas sebuah gagasan. Tapi juga memang perlu diwaspadai, sebab gagasan, mau seorisinal apa tetap tidak lahir dari ruang hampa. Ia mengandung keresahan, harapan, idealisme, bahkan kegilaan pemikirnya. Sekali lagi saya memuji Tuhan atas ini semua, dunia sungguh indah.
Oleh karenanya penting kiranya sesekali kita menimbang kebenaran tidak hanya atas dasar koherensinya diatas kertas buku-buku pedoman para akademisi, yang lantas secara kaku disuarakan didepan gedung istana negara maupun gedung anggota dewan. Tapi juga atas dasar pragmatisme sebuah gagasan. Ingat, manusia tetap manusia, siapapun itu. Prilakunya tidak selogis pikirannya. Banyak pertimbangan yang dilalui. Istri cerewet, anak banyak maunya, pemodal yang suka menuntut kebijakan ini dan itu, instruksi pimpinan partai, dan masih banyak lagi modal kampanye yang belum kembali. Ah, suram sekali sepertinya. Tapi itulah dunia manusia yang memang takdirnya ditulis suka berkomplot dan saling mengalirkan darah.
Lantas dimana letak ikhlas jika ketulusan sebenarnya hanyalah tukar tambah kepentingan?. Kita rela menghutangi orang lain agar saat kita berhutang ia mau menghutangi kita di suatu hari nanti. Kita berteman karena ada sisi yang bisa kita manfaatkan, kita menjalin hubungan asmara agar kita mempunyai orientasi seksual, baik secara nyata maupun imajinatif, kita bertegur sapa dengan orang lain agar orang lain simpati, kita mengajar agar status sosial keluarga dapat terjaga, bahkan kita belajar agar bahagia. Semua prilaku kita memang dipenuhi motif yang titik akhirnya adalah kebahagiaan dan kenyamanan secara individu. Maka inilah yang menarik dari Tuhan. Ah, Tuhan maha asyik memang, kata Mbah Tedjo. Ikhlas didefinisikan sebagai prilaku hati yang menjadikan Tuhan sebagai orientasi dan kepentingan utama dalam segala tindak laku.
Dalam hal ini ikhlas berarti suatu pengalaman psikologis keterikatan dan keberhambaan manusia pada Tuhan. Ia menomor duakan kepentingan manusiawinya dengan menjadikan Tuhan sebagai orientasi utama. Secara ajaib juga orientasi ketuhanan ini hilang secara tiba-tiba ketika dalam prilaku kita terdapat kepentingan yang batil, atau bentuk prilaku kita memang sebuah kejahatan. Jangan harap ada nilai keikhlasan dalam korupsi. Dari sini saya paham bahwa Tuhan adalah cahaya. “Allahu nurus samawati wal ardl”, kata Qur’an. Tuhan adalah cahaya langit dan bumi, kemungkinan terakhir, dan jalan keluar kerumitan dunia manusia. Mau sepolitis apapun langkah kita, jika orientasinya adalah Tuhan pasti hasilnya baik. Mau model kurikulum apapun pendidikan kita, jika orientasinya adalah Tuhan, bukan lapangan pekerjaan, pasti hasilnya baik. Bahkan entah darimana sumbernya, dengan Tuhan sebagai orientasi utama manusia lebih kuat secara mental, lebih berbahagia, dan tentunya lebih produktif. Ah, Tuhan maha asyik.
Perkongsian antara paradigma pendidikan dengan bisnis perketelaan tentunya tak lepas dari hal ini. Secara kausalitas psikologis kemanusiaan sangat memungkinkan jika nantinya keras atau lembeknya pandangan-pandangan saya akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pengasuh pesantren. Setali tiga uang juga sangat memungkinkan jika laris tidaknya produk ketela saya akan sangat ditentukan oleh hubungan pengasuh dengan saya. ya, memang begitulah dunia manusia, sangat rumit. Tapi tentunya jika orientasi masing-masing dari kita adalah Tuhan, saya yakin semua itu bukanlah masalah besar. Bagi orang yang mencapai karakter hati ikhlas pastinya dapat dengan mudah mencerna ucapan Sayyid Ali R.a “man lam yakhofillah yakhof kulla syai’in, wa man yakhofillah yakhofhu kullu syai’in”. Barang siapa tidak takut pada Allah maka ia akan mudah takut dan khawatir terhadap segala sesuatu, dan barangsiapa takut pada Allah maka ia akan ditakuti oleh segala sesuatu. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dunia tak akan pernah ideal, sebab bentuk ideal dunia adalah ketidak idealannya itu sendiri. Di dalamnya terdapat orang yang sudah mapan secara mental, ada yang masih belajar, dan ada yang baru mengenal. Keseimbangannya kita yang berusaha menjaga, semoga Tuhan mentakdirkan yang terbaik untuk kita.